
Desa Bobawa
Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada
Jeritan Hati Rakyat: BBM di Ujung Asa
Kabut pagi di Bajawa turun lebih tebal dari biasanya. Jalanan basah oleh embun, namun di ujung jalan sudah terlihat puluhan kendaraan mengular. Mesin-mesin mati, hanya suara batuk sopir dan derit sandal para pengantre yang terdengar.
Markus berdiri di samping motornya yang sudah tiga hari tak terisi bensin. Tangannya dingin memegang botol bekas air mineral—harapan terakhir kalau-kalau petugas SPBU mengizinkan membeli secukupnya.
“Pak, antre dari jam berapa?” tanya seorang ibu muda di belakangnya, menggendong bayi yang sesekali menangis.
“Jam lima pagi, Bu… tapi ini sudah jam delapan, belum juga jalan. Kalau habis lagi, saya tak tahu harus bilang apa ke anak di rumah,” jawab Markus lemah.
Di deretan depan, Yohan, sopir angkot, mulai bersuara lantang.
“Kita ini manusia atau bukan? Masa di daerah sendiri, beli bensin seperti minta belas kasihan?!”
“Betul!” sahut warga lain. “Kalau kapal telat, kita yang menderita. Kalau harga naik, kita juga yang sengsara!”
Petugas SPBU yang mendengar itu hanya bisa mengangkat bahu. “Maaf, Pak. Ini bukan salah kami. Kiriman BBM belum datang. Kapal katanya tertahan cuaca.”
Markus menatap petugas itu lama. Bukan marah, tapi putus asa. “Pak… kami ini bukan mau marah. Kami cuma mau hidup. Tanpa BBM, motor saya tak bisa jalan, kopi saya busuk di kebun. Anak saya makan apa?”
Angin dingin membawa aroma bensin yang tipis, tanda tangki SPBU hampir kosong. Barisan antrean mulai gelisah. Beberapa orang berlari ke pengecer di tepi jalan, tapi harga di sana gila—dua kali lipat.
Di warung kopi tak jauh dari SPBU, Markus duduk dengan Yohan dan beberapa warga.
“Kemarin saya harus pinjam motor tetangga untuk antar istri melahirkan ke puskesmas,” kata Yohan pelan. “Itu pun bensinnya setengah mati dicari. Kalau terlambat sedikit, mungkin saya sudah kehilangan istri dan anak saya.”
Seorang bapak tua menimpali, “Saya tak pernah sekolah tinggi, tapi saya tahu… di negara kaya minyak, rakyat seharusnya tak menangis untuk setetes bensin.”
Markus meremas gelas kopinya. “Besok saya coba lagi. Kalau habis lagi, entah apa yang akan saya lakukan.”
Esoknya, ia kembali antre sejak subuh. Kabut belum terangkat, namun suara ribut sudah terdengar.
“Habis! Habis!” teriak seseorang dari depan. Gelombang kekecewaan langsung menyapu antrean. Ada yang marah-marah, ada yang membanting helm, ada yang hanya terduduk memegang kepala.
Markus berdiri kaku. Botol kosong di tangannya terjatuh. Matanya panas. Dalam kepalanya, wajah anak-anaknya terbayang—menunggu sarapan, menunggu ayahnya membawa kabar baik.
Ia melangkah pelan keluar dari antrean. Di langit, matahari mulai menembus kabut, tapi baginya sinar itu terasa hambar.
Di ujung jalan, ia berbisik pada dirinya sendiri, namun cukup keras untuk didengar orang di sekitarnya:
“Jeritan kita tak pernah sampai ke telinga yang berkuasa… tapi kita akan terus berteriak, karena diam berarti mati.”


























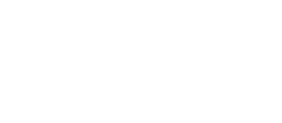
Desago
11 Agustus 2025 08:43:11
Salut untuk Desa Bobawa yang meluncurkan website berbasis Opensid, wujud nyata transparansi dan kemajuan...